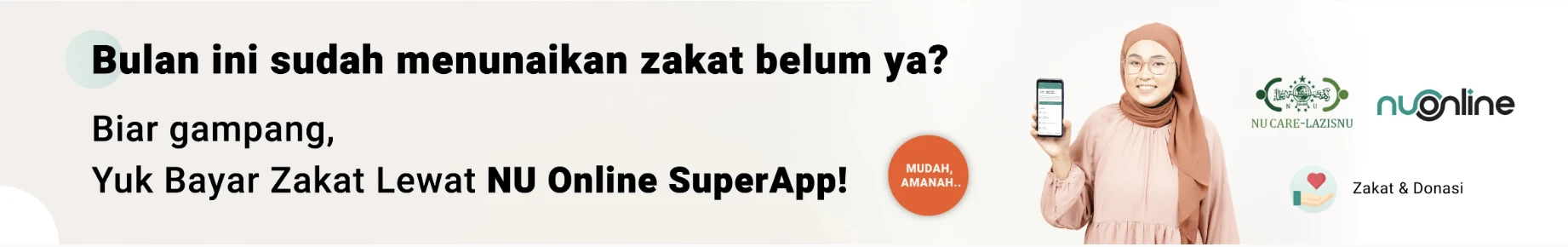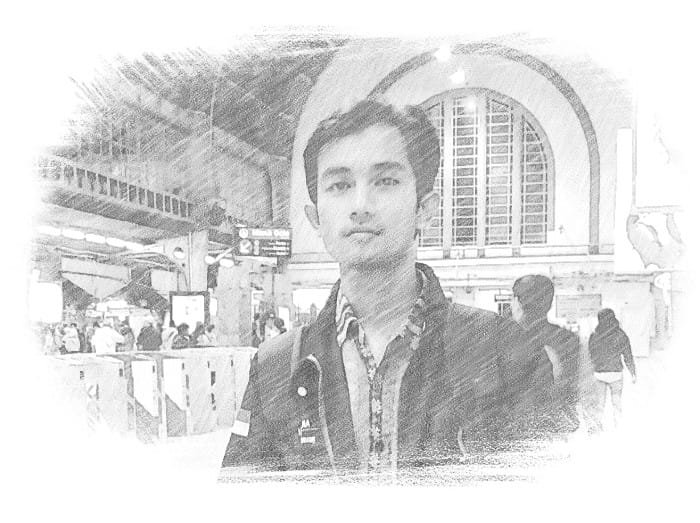Oleh: Maulana Al Fatih*
Tak terasa, Idul Adha telah tiba dan kembali menyapa. Gema takbir berkumandang, bersahutan di segala penjuru dunia. Di desa-desa maupun kota, semua haru menyambutnya. Meskipun dengan nuansa yang sedikit berbeda karena pandemi yang tak kunjung reda.
Dua tahun sudah umat Islam merayakan Idul Adha di tengah merebaknya Covid-19. Sejak merebak di Indonesia pada sekitar awal tahun 2020 lalu, sontak merubah semua dinamika kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam hal menjalankan ibadah keagamaan atau hari raya. Dari harus bermasker, menjaga jarak, dan segala tetek bengeknya.
Perubahan pola itu juga sedikit banyak memangkas intensitas pertemuan dalam sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahkan memunculkan ketimpangan sosial. Dan di momentum Idul Adha inilah, ketimpangan itu mesti diuraikan. Bisa dibilang, inilah momentum mengetuk nurani si kaya agar peduli ke yang melarat, menghapus sekat-sekat sosial diantara keduanya. Agar semakin muncul kesadaran bahwa manusia memang benar-benar mahluk sosial yang ketika mati, tidak lantas bisa jalan sendiri ke kuburan.
Idul Adha yang terdapat ibadah kurban di dalamnya, sayogyanya tidak melulu bagian dari ekspresi ketaqwaan seseorang. Taqwa juga tak sesempit dimaknai dengan menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Lebih jauh lagi, harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan (Hablum Minallah) dan dengan sesama manusia (Hablum Minannas).
Sedekah daging kurban memang membutuhkan biaya tidak sedikit, dan membutuhkan keikhlasan. Bagi sebagian orang mungkin nilainya tidak seberapa dan mudah melakukan kurban. Belajar dari sejarah, Nabi Ibrahim ikhlas dan bersedia mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Dari situ, ketabahan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan sesuatu yang berharga dari dirinya (anak) menjadi wujud nyata bagaimana ikhlas sebenar-benarnya ikhlas tersebut. Dan Allah SWT membalasnya dengan mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing dari surga. Jika ditarik dalam kehidupan yang luas, pengorbanan tak harus dilakukan saat telah memiliki kelebihan ataupun mampu, namun sejauh mana bisa mengorbankan sesuatu tanpa embel-embel mengharapkan imbalan.
Karena itu, sedekah daging kurban yang diberikan kepada kalangan fakir, miskin, dan orang-orang kurang mampu, ataupun masyarakat umum, secara dhohir, hal itu memang membantu sesama. Tapi sejatinya, daging-daging kurban yang dibagikan itu memiliki spirit atau semangat yang bermuara pada tujuan: jangan ada lagi cerita orang miskin kelaparan, atau tidak bisa makan.
Spirit inilah yang perlu terus dirawat. Lebih tepatnya wajib diteruskan. Momentum kurban boleh lewat, dan datang di tahun-tahun berikutnya, tapi spirit ‘ngopeni’ ini harus berlanjut bahkan dibudayakan. Andai kata semangat saling ngopeni ini terbangun setiap hari dalam kehidupan bersosial, bukanlah sebuah kemustahilan, ketimpangan sosial itu perlahan terkikis. Dan berganti menjadi kehidupan masyarakat yang saling menjaga dan menolong sesama. Sebagai hamba Tuhan, dan sebagai mahluk sosial.
Inilah wujud taqwa sosial itu. Masyarakat saling menjaga dan saling membantu satu sama lain, ikhlas dan bersedia untuk saling memberi tanpa mengharap kembali. Mungkin membangkitkan kesadaran sosial semacam itu sulit terjadi dan tidak mudah, namun bukan berarti mustahil. Semua bisa dimulai dari masing-masing pribadi, keluarga, kolega, tetangga, dan kepada orang-orang yang dirasa tak seberuntung seperti orang kebanyakan. Memulainya dengan saling memberi manfaat dan bermanfaat untuk yang lainnya. Khairunnas anfauhum linnas. Wallahu A’lam Bissawab.
*Maulana Al Fatih, Pimpinan Redaksi di Media PCNU Jember ( pcnujember.or.id )